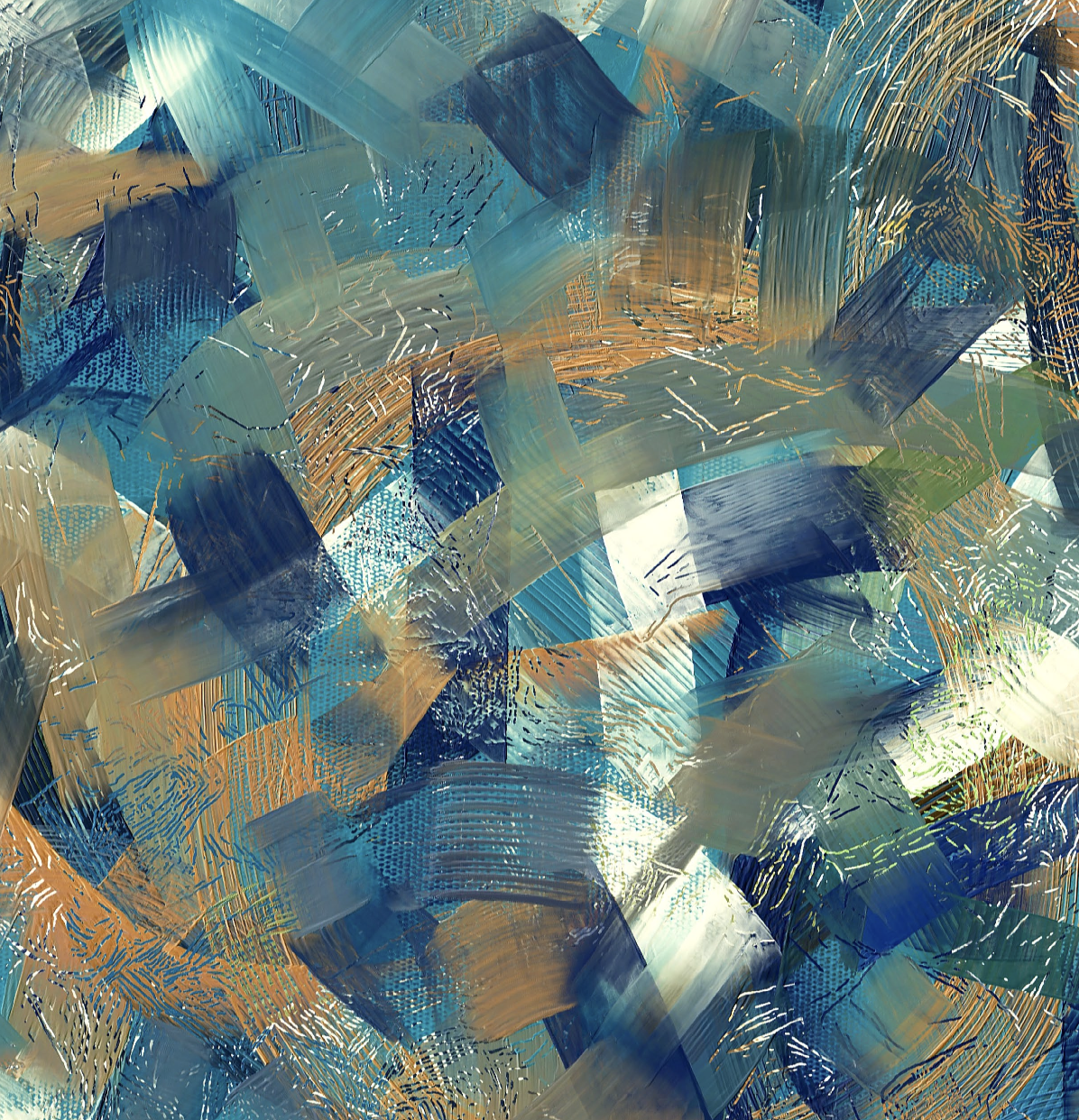Reformasi kemanusiaan mengalami pasang surut.
Dominasi pendekatan terpotong-potong yang tidak menyasar akar masalah dan keinginan donor untuk mempertahankan kekuatan kendali menjadi hambatan mencapai visi perubahan sistem kemanusiaan yang terpusat dari atas ke bawah. Terkait hal ini, perubahan cepat yang tidak terhindarkan oleh pandemi COVID-19 terbukti menjadi game changer. Seperti disebutkan oleh The New Humanitarian dalam ringkasan tren kebijakan tahun 2020 , ‘Upaya menuju reformasi itu ibarat suatu perabot yang senantiasa ada di sektor kemanusiaan, tetapi perubahannya lambat.’
Mungkinkah ini terjadi karena selama ini kita mencari jawaban di tempat yang salah? Tahun 2018, ketika tsunami melanda pulau Sulawesi di Indonesia, responnya jelas menunjukkan kepemimpinan dan peran operasional pelaku nasional dan lokal, baik pemerintah maupun masyarakat sipil. Penelitian oleh Humanitarian Advisory Group (HAG) dan Pujiono Centre pada tahun berikutnya menunjukkan bahwa ‘ Jadwal pergeseran kekuasaan di kawasan ini tidak lagi ditentukan oleh sistem internasional. Implikasi pentingnya adalah, bahwa sistem internasional perlu lebih cepat berubah untuk menyesuaikan diri dengan norma yang baru atau menghadapi risiko untuk menjadi mubazir dan terkesampingkan. ‘
Pergeseran ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari perjuangan dan perundang-undangan yang berkelanjutan selama dua puluh tahun terakhir, sebagaimana diulas dalam laporan baru HAG dan Pujiono Center tentang reformasi di Indonesia. Sebagai bagian dari Building a Blueprint for Change, suatu upaya untuk mendorong katalisasi perubahan dari bawah ke atas. Upaya ini memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika lokal pada kurun tertentu. Laporan ini mencatat kejadian-kejadian bencana besar dan peristiwa kemanusiaan di Indonesia serta pada tataran global yang berpeluang mempengaruhi perubahan sistem kemanusiaan tingkat negara.
Tsunami Samudra Hindia 2004 – atau lebih tepatnya, respon kemanusiaan sesudahnya yang didominasi pelaku internasional – mengkatalisasi sejumlah reformasi besar pada sistem kemanusiaan di Indonesia dan secara global. Sembilan puluh satu persen orang yang terdampak tsunami di Indonesia melaporkan bahwa mereka diselamatkan oleh orang-orang disekitarnya. Pada 48 jam pertama nyaris tidak ada bantuan dari luar. Namun setelah itu diperkirakan 400 organisasi internasional non-pemerintah dengan 5.000 staf asing tiba di Aceh, banyak yang tidak ada sangkut paut sebelumnya dengan wilayah ini dan hanya punya secuil pemahaman kontekstual. Respon yang dilakukan tumpang tindih, top-down, tidak tanggap terhadap prioritas nasional dan lokal, dan eksploitatif terhadap kepakaran lokal.
Respons tsunami ini merupakan titik balik hubungan respon kemanusiaan antara Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional. Keadaan ini, pada gilirannya, memberikan momentum bagi upaya masyarakat sipil Indonesia yang ketika itu sedang melakukan reformasi legislatif, dan berujung pada pengesahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007. Undang-undang ini meluncurkan suatu proses, yang juga terus diperbaiki sambil berjalan, untuk membuat suatu penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan lebih selaras dengan pengurangan risiko bencana, dengan penguatan pihak pemerintahan.

Masyarakat sipil Indonesia terus berperan penting dalam mendorong reformasi dan sejak itu semakin diakui perannya dalam penanggulangan bencana. Evaluasi Tim Mitra Kemanusiaan (HCT) atas respon bencana baru-baru ini menggarisbawahi bagaimana peran pelaksana para pelaku lokal menjadi semakin menonjol, sementara juga menunjukkan perlunya lebih banyak investasi pada sistem dan proses lokal. Setelah kejadian gempa Sulawesi Tengah pada tahun 2018, pemerintah menyatakan diperlukannya pembatasan kehadiran staf asing dengan tujuan mengkoordinasikan bantuan internasional, seperti dijelaskan oleh juru bicara BNPB: ‘membiarkan orang asing memasuki daerah yang terkena bencana tanpa batasan dan manajemen yang jelas hanya akan menambahkan lebih banyak pekerjaan kepada gugus tugas pemerintah.‘ Dengan terputusnya akses, badan-badan internasional dipaksa menyampaikan bantuan mereka dalam peran mereka sebagai pendukung, sementara LSM nasional membantu organisasi -organisasi lokal mengendalikan risiko keuangan dalam penyaluran dana bantuan.
Sampai sekarang, nyaris tidak ada tanda bahwa bahasa Grand Bargain digunakan secara meluas pada sektor kemanusiaan di Indonesia, yang tengah berjuang di bawah himpitan ganda dari bencana yang kerap terjadi dan pandemi COVID-19. Dampak mengerikan di dalam negeri ini terlampau besar untuk diabaikan apalagi kalau cuma untuk terlibat dalam percaturan global, tentang istilah Pelokalan, misalnya. Meskipun demikian, keliru kiranya kalau menyikapi ‘lokal’ dan ‘global’ sebagai pengertian yang terpisah dan tidak saling terhubung ketika dirujuk pada sejarah. Selama reformasi yang berlangsung bertahun-tahun ini, tengah terjadi pengaruh timbal balik antara para pelaku kemanusiaan, termasuk pemerintah, di dalam dan di luar Indonesia. Misalnya, tsunami 2004 memicu reformasi besar-besaran di tingkat internasional; demikian juga pendekatan Pemerintah Indonesia pada undang-undang 2007 dipengaruhi oleh Kerangka Aksi Hyogo tentang ketangguhan bencana. Peningkatan kerja sama dan kepemimpinan regional menjadikan AHA Centre dari ASEAN lebih aktif mendukung koordinasi pada beberapa respon bencana baru-baru ini.
Organisasi seperti NEAR dan Ground Truth Solutions mengadvokasi agar reformasi sistem kemanusiaan didekati dari perspektif komunitas yang terdampak krisis. Namun tetap ada kecenderungan merepresentasikan proposal yang keluar dari forum kebijakan internasional di Jenewa atau New York sebagai kontribusi pada ‘perubahan sistem’, sementara perkembangan yang didorong oleh inisiatif kebijakan nasional cenderung dilihat sekedar ‘perubahan konteks’ . Sikap ini bukti keinginan melanggengkan sejarah ketidaksetaraan yang mengakar terkait siapa yang senantiasa menjadikan prioritasnya dalam upaya mereka ‘mengatur dunia’ sementara mereka menafikan pengaruh timbal balik yang telah terjadi pada titik-titik krusial sepanjang proses perubahan ini.
Pandemi COVID-19 mengungkapkan kesenjangan lebar pada sistem kemanusiaan global dan mendorong momentum dan pembahasan tentang reformasi. Menjelang putaran Grand Bargain berikutnya, penting sekali kiranya menggali hubungan antara proses lokal, nasional dan global untuk memahami bagaimana reformasi telah terjadi selama ini. Dengan menyoroti bagaimana reformasi berbasis negara menanggapi dorongan dan prioritas tertentu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang dipimpin oleh pelaku lokal dan menyediakan basis bukti untuk menggelar visi perubahan dan prospek keberhasilannya.
Credits: SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo, Bascar / Shutterstock